SAYA merasa gembira karena dikaruniai Tuhan seorang istri yang cantik, putih, langsing, sabar, soleh, seorang muslimah dan berkerudung.Isteri saya masih keturunan asing. Ayahnya Amerika dan ibunya Jawa.. Semua anak saya mirip ibunya, mirip bule.
Saya juga dikaruniai tiga orang anak cantik bernama Rina berumur lima tahun, Rani berumur empat tahun dan Rini berumur tiga tahun. Lengkapnya Rina Ekawati, Rani Dwiwati dan Rini Triwati. Semua anak saya bernama Indonesia.
Saya tidak mau ikut-ikutan seperti muslim lainnya di mana anak-anaknya diberi nama Arab atau diambil dari bahasa Arab. Mereka adalah muslim-muslim yang tidak bisa menghargai budaya Indonesia.
Sekaligus saya juga sedih, karena ketiga anak saya yang masih kecil ternyata menderita autis.
“Autis itu apa sih, Mas? Apakah termasuk sakit jiwa?”. Sepulang konsultasi dari dokter, istriku yang bernama Paramitha itu bertanya kepada saya. Saat itu kami berdua sedang menuju pulang naik taksi Blue Bird lengkap bersama Rina, Rani dan Rini.
“Oh, bukan sakit jiwa. Autisme itu merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang berat, yang timbul dalam tiga tahun pertama kehidupan anak. Autisme berasal dari bahasa Yunani yaitu “autos” atau “sendiri” yang diartikan memiliki keanehan dalam bersosialisasi dengan dunia di luar dirinya.
Banyak penderita dengan sindrom ini memiliki inteligensi rata-rata atau sering kali juga di atas rata-rata, tetapi umumnya mereka sudah didiskreditkan sejak awal. ” Saya menjelaskan.
“Ada penjelasan lainnya, Mas? Saya kok kurang faham”. Istriku semakin ingin tahu.
“Ada. Autisme sebagai cacat pada perkembangan syaraf dan psikis manusia, baik sejak janin dan seterusnya, yang menyebabkan kelemahan dalam berinteraksi sosial, kemampuan berkomunikasi, perbedaan pola minat dan tingkah laku. Autisme cukup luas dan mencakup banyak hal. ”
“Gejala-gejalanya bagaimana sih, Mas?”. Mitha ingin tahu.
“Begini. Gejala-gejala bisa terlihat sejak beberapa hari/minggu setelah bayi lahir, atau beberapa bulan kemudian setelah tahap-tahap perkembangan yang seharusnya ada tetapi tidak dicapai oleh balita yang bersangkutan.
Ada juga anak-anak yang mula-mula perkembangannya tampak normal, tetapi kemudian terjadi kemunduran pada umur 18 bulan, yaitu berbagai kemampuan yang tadinya sudah ada, misalnya sebelumnya anak sudah berbicara sepatah-dua-patah kata, tetapi kemudian menghilang. ”. Sayapun menyebut nama Rini, si bungsu yang kehilangan suara. Tak mampu berkata banyak. Suaranya pun lirih tak jelas. Ciri khas anak autis yaitu selalu berusaha menghindari kontak mata dengan orang lain”
Taksi terus meluncur di kawasan Tebet menuju rumah saya.
Sayapun melanjutkan penjelasan ke Mitha soal autis. Kebetulan dulu saya pernah kuliah di Fakultas Kedokteran, Universitas Trisakti, Jakarta. Semester enam gagal, kemudian pindah ke Fakultas Ekonomi, di Universitas Trisakti juga.
“Autis bukan sakit jiwa. Tetapi suatu kelainan yang dianggap tidak bisa disembuhkan. Namun dengan terapi dan penanganan yang optimal, anak-anak kita mudah-mudahan bisa disembuhkan”
“Pasti bisa disembuhkan, Mas?” Istriku kurang yakin.
Maklum, ibu mana yang tidak sedih melihat anak-anaknya menderita autis? Semula Mitha tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun, saya selalu memberikan keyakinan bahwa suatu ketika anak-anak akan sembuh. Untuk itulah, atas nasehat dokter, saya menyewa tenaga terapis untuk datang ke rumah tiga kali seminggu untuk memberikan terapi kepada Rina, Rani dan Rini.
Saya menyadari bahwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tiap tahun penyandang autis jumlahnya terus meningkat. Anak autis memang mempunyai tingkah laku yang lain daripada anak-anak normal lainnya. Anak-anak autis adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan lebih.
“Jangan sekali-kali memarahi anak-anak ya, Ma. Betapapun nakalnya mereka”. Pesan saya ke isteri ketika taksi sudah sampai di rumah. Sesudah membayar taksi, saya, Mitha dan ketiga anak-anakpun masuk ke rumah.
Sejak ada anak-anak autis ini memang rumah saya berantakan. Jemuran diobrak-abrik anak-anak. Di ruang tamu ada sapu, ada ember, boneka dan barang apa saja. Kalau nonton televisipun rebutan. Ada yang suka filem kartun, ada yang suka musik dan ada yang suka balap motor atau mobil. Bisa dibayangkan betapa ribut dan kotornya rumah kami ini.
Tiap kali saya mau berangkat kantor, Mitha pasti menangis. Sedih, karena bertahun-tahun harus hidup menderita karena punya anak-anak autis. Selalu jadi bahan pembicaraan dan cibiran para tetangga. Maklum, ketiga anak kami memang juga sering mengganggu tetangga. Nakal, tetapi nakalnya keterlaluan. Misalnya, suka membuang sampah yang semula ada di tempat sampah, dilemparkan ke rumah-rumah tetangga.
Pernah Mitha ribut dengan tetangga gara-gara Rina ditampar seorang ibu rumah tangga karena Rina merobohkan dengan sengaja jemuran ibu itu. Keluhan juga banyak diterima para tetangga. Sejak itu, anak-anak tidak boleh keluar. Pintu pagar ditinggikan dan digembok.
Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Tanpa terasa sudah sepuluh tahun anak-anak kami mendapatkan terapi. Namun hasilnya tidak ada. Bahkan mereka hanya sanggup duduk hingga lulus SD. Kata dokter, itu sudah hebat. Yang mengherankan, anak tante saya yang juga autis, ternyata bisa disembuhkan. Sedangkan anak-anak kami tetap autis hingga usia remaja.
Lantas, terjadilah sebuah hal yang tak pernah saya bayangkan. Ketika saya sedang bekerja, tiba-tiba ada tetangga menelepon agar saya segera pulang karena Mitha sakit keras. Sakit keras apa? Sewaktu saya berangkat kantor istriku sehat-sehat saja, kok. Sayang, di rumah saya belum pasang telepon sehingga saya tidak bisa mencek kebenaran informasi itu.
Akhirnya, dengan mengendarai mobil Daihatsu Espass kesayangan saya, yang baru saya ambil dari bengkel, sayapun segera pulang. Waktu itu sekitar pukul 11:00 WIB. Sampai di rumah saya lihat sudah banyak orang berkumpul.
Begitu saya masuk kamar, saya menemukan Mitha di tempat tidur dalam keadaan kaku, tubuhnya membiru dan dari mulutnya keluar buih. Mitha telah bunuh diri. Oh, Tuhan!
Saya menutup muka dengan kedua telapak tangan saya. Saya menangis. Kemudian mencium pipi istri tercinta yang sudah tak bernyawa lagi. Anak-anak menangis sedih. Hanya selembar surat yang ditinggalkan Mitha. Isinya, Mitha tak tahan lagi mengalami penderitaan seperti itu. Dia tak bisa menerima kenyataan punya tiga anak penderita autis.
Istriku, Paramitha, seorang muslimah yang tidak mau menerima kenyataan hidup. Tak tahan menerima cobaan dari Tuhan. Tak menyadari bahwa semua orang di dunia, tanpa terkecuali, pasti menghadapi berbagai macam cobaan
Saya baca surat dari Paramitha yang ditulis sebelum meninggal.
“Mas, tolong anak-anak dijaga baik-baik. Saya tidak tahan lagi. Maafkan saya, Mas…”
Sementara itu, ketiga anak saya terus menangis di dekat jenasah ibunya.
Hariyanto Imadha
Penulis Cerpen
Sejak 1973
Filed under: Uncategorized | Tagged: budaya, cerita, cerpen, fakultas, fibui, fsui, hariyanto imadha, ilmu, indonesia, pendek, rani, rina, rini, sastra, ui, universitas |



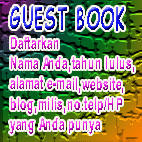

















Semua komentar otomatis akan dihapus